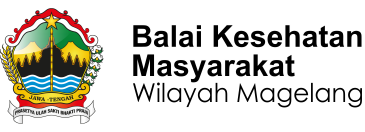Janji kemajuan teknologi serta semangat keterbukaan yang digaungkan era digital ternyata membawa realita menuju simulakra. Benar, kekerasan berbasis gender justru menemukan ruang baru untuk tumbuh dan menyebar. Ruang digital yang semestinya menjadi perluasan ruang publik yang aman dan setara kini berubah menjadi arena kontestasi kekuasaan, bias, dan kekerasan simbolik. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tidak bisa hanya dipahami sebagai gangguan sesaat atau penyimpangan perilaku, melainkan sebagai refleksi dari struktur sosial, politik, dan kultural yang lebih luas. Untuk memahami dan menjawab persoalan ini secara utuh, kita perlu mendekatinya melalui lensa interdisipliner. Sains menjelaskan mekanisme biologis dan psikologis dari trauma yang terjadi. Filsafat memberi landasan etis tentang tanggung jawab kolektif. Teknologi menawarkan solusi sekaligus tantangan struktural. Sementara feminisme dan keadilan sosial menegaskan siapa yang paling terdampak, dan mengapa mereka kerap dibungkam. Dengan pendekatan inilah kita dapat menelusuri bagaimana dunia maya menciptakan luka yang nyata, dan bagaimana jalan keluar harus dibangun melalui pemahaman yang saling terhubung dan berpihak pada kemanusiaan.
Dunia Maya, Luka Nyata
Era digital menyediakan panggung interaksi sosial. Konektivitas itu juga melahirkan paradoks memilukan. Teknologi yang menjanjikan pencerahan justru menjadi alat untuk melanggengkan kekerasan berbasis gender. KBGO seolah menjelma simtomatologi zaman yang memanifestasikan ketimpangan lama dalam realitas baru. Dari pelecehan daring hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan, KBGO melampaui sekadar “masalah internet”—ia adalah pertarungan nilai, etika, dan kemanusiaan yang nyata.
Dari Ruang Domestik ke Arena Digital
Dari perspektif historis, KBGO bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari kekerasan berbasis gender yang telah mengakar selama berabad-abad dalam sistem patriarkal. Ruang digital, seperti yang ditunjukkan oleh transisi dari milenium baru ke era media sosial, hanya memperluas panggung ekspresi kekuasaan dan dominasi.
Revolusi digital menciptakan ilusi ruang netral, namun pada kenyataannya, media sosial menjadi arena baru di mana kekuasaan diekspresikan dalam bentuk ujaran kebencian dan kontrol terhadap tubuh serta citra perempuan dan kelompok minoritas gender. Ini bukan hanya soal teknologi, melainkan kelanjutan narasi historis tentang siapa yang punya suara, dan siapa yang dibungkam.
Luka Psikis dalam Dunia yang Tidak Terlihat
Ilmu kedokteran dan psikologi menegaskan bahwa trauma digital meninggalkan jejak yang tak kalah serius dibanding luka fisik. Korban KBGO mengalami peningkatan gangguan kecemasan, depresi, hingga PTSD. Namun yang membuatnya unik dan ironis: traumanya tak memiliki “lokasi geografis” yang jelas. Dunia digital bersifat ubikuitas—ada di mana-mana, sekaligus tak terlihat.
Stres kronis yang ditimbulkan oleh paparan konten kekerasan dan komentar merendahkan berdampak pada fungsi sistem kekebalan tubuh dan kesehatan jantung. Ini adalah epidemi diam (silent epidemic), sebagaimana disebut WHO, yang luput dari perhatian sistem layanan kesehatan konvensional.
Trauma Digital dan Biokimia Ketakutan
Dari kacamata neurosains, respons otak terhadap ancaman digital menyerupai respons terhadap ancaman fisik: sistem limbik aktif, amigdala menyala, dan kortisol memuncak. Namun, yang membedakannya adalah durasi: konten digital bisa berulang tanpa henti. Dengan kata lain, KBGO bukan hanya kejadian satu kali, tetapi rangkaian pemicu stres yang berulang—membuat otak berada dalam mode waspada kronis.
Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa korban KBGO mengalami beban kognitif tinggi karena otaknya terus-menerus berupaya memproses dan memitigasi ancaman yang tak kasatmata. Ini menjelaskan kenapa banyak korban merasa “lelah secara eksistensial”, bukan hanya emosional.
Wajah Pelaku dan Perilaku Anonimitas
KBGO juga harus dipahami dari sisi pelaku. Teori deindividuasi menjelaskan bagaimana anonimitas digital menghapus rasa tanggung jawab. Orang biasa, ketika bersembunyi di balik layar, dapat berubah menjadi pelaku kekerasan. Ini mencerminkan kegagalan sistem edukasi sosial dalam menanamkan empati dan literasi etika digital.
Korban, sebaliknya, mengalami disonansi identitas—terutama remaja—karena ruang digital adalah ruang eksplorasi diri. Ketika ruang ini berubah menjadi tempat penghakiman, pertumbuhan psikologis mereka terganggu.
Hak atas Keamanan dalam Dunia Virtual
Apakah kita punya “hak untuk merasa aman” di dunia digital? Filsafat politik modern, seperti dikemukakan Habermas, mengidealkan ruang publik yang rasional dan setara. Namun realitas digital kita justru menciptakan ruang publik yang penuh kebisingan, bias, dan kekerasan simbolik.
Feminisme post-strukturalis, seperti yang dikemukakan oleh Judith Butler, membaca KBGO sebagai “kekerasan performatif”—cara sistem mempertahankan dominasi dengan cara simbolik. Maka, pertarungan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang etika dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ruang yang etis dan adil.
Narasi yang Menindas, Narasi yang Membebaskan
Budaya digital membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan merespons kekerasan. KBGO terjadi dalam konteks narasi budaya yang mengakar: perempuan diposisikan sebagai objek, dan kekerasan sering kali dinormalisasi atau dijustifikasi. Media, film, hingga meme ikut melanggengkan bias ini.
Namun, di sisi lain, narasi juga menjadi alat perlawanan. Kampanye seperti #MeToo menunjukkan kekuatan storytelling dalam membuka ruang kesaksian dan solidaritas. Humaniora memberi kita alat untuk membaca, menafsirkan, dan mengubah wacana.
Teknologi: Antara Ancaman dan Harapan
Teknologi bukan entitas netral. Algoritma yang kita pikir objektif sering kali memperkuat bias yang ada. Studi mutakhir menunjukkan bahwa sistem moderasi otomatis masih gagal mengenali ujaran misoginis karena dilatih pada data yang bias gender.
Namun, harapan juga datang dari teknologi: AI yang dirancang dengan perspektif feminis dapat membantu mengenali pola kekerasan. Blockchain dapat memberi kendali pada korban atas distribusi data mereka. Teknologi, seperti pisau, bisa melukai—tetapi juga bisa menyelamatkan, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa.

Problematika Kompleks: Ketika Sistem Tak Siap
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mencerminkan gejala ketimpangan sistemik yang jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan perilaku individu di ruang digital. Ia menunjukkan kegagalan kolektif—baik negara, masyarakat, maupun platform teknologi—dalam merespons perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Salah satu akar masalah utama adalah ketertinggalan regulasi dari laju inovasi digital. Hukum yang ada, seperti UU ITE di Indonesia, belum secara spesifik mengakui dan mengatur bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di internet, termasuk revenge porn, doxxing, atau penyebaran konten intim non-konsensual. Ketika hukum tertinggal, korban kehilangan rute formal untuk mendapatkan keadilan, sementara pelaku beroperasi dengan rasa impunitas yang tinggi.
Masalah ini diperparah oleh budaya patriarki yang masih sangat kuat di banyak masyarakat. Nilai-nilai konservatif yang melekat pada moralitas gender sering digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender, dengan dalih norma kesopanan, kehormatan keluarga, atau “kelayakan sosial”. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan dan distigmatisasi, sementara pelaku dilindungi oleh struktur sosial yang permisif terhadap kekerasan simbolik dan seksual. Perspektif ini tidak hanya merugikan perempuan dan kelompok LGBTQ+, tetapi juga menutup kemungkinan terjadinya reformasi kultural yang inklusif.
Ketimpangan digital menjadi faktor ketiga yang memperdalam jurang kerentanan. Akses terhadap teknologi informasi yang tidak merata membuat kelompok tertentu—seperti perempuan di pedesaan, penyandang disabilitas, atau komunitas queer—mengalami hambatan ganda: mereka lebih rentan menjadi korban dan sekaligus kurang memiliki sumber daya untuk membela diri. Rendahnya literasi digital dan ketidaksetaraan infrastruktur menjadikan mereka semakin tersingkir dari sistem perlindungan digital yang seharusnya bersifat universal.
Lebih jauh lagi, model bisnis platform digital saat ini justru memonetisasi konflik, provokasi, dan konten ekstrem. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan untuk melindungi pengguna. Akibatnya, ujaran kebencian, pelecehan seksual, dan konten misoginis sering kali tidak hanya lolos dari moderasi, tetapi juga mendapatkan sorotan karena dianggap “menarik” secara komersial. Ini menunjukkan bahwa masalah KBGO tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan moral, tetapi harus melalui pembenahan struktural terhadap cara kerja ekonomi digital.
Untuk keluar dari kebuntuan ini, diperlukan pendekatan integratif dan solutif. Pertama, regulasi perlu direformasi dengan perspektif keadilan gender dan kecepatan adaptasi teknologi, termasuk pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi yang sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender. Kedua, perlu ada gerakan budaya untuk menantang norma patriarki dan membangun solidaritas digital yang berpihak pada korban, bukan pada pelaku. Ketiga, akses dan literasi digital harus diperluas secara inklusif, dengan dukungan negara dan sektor swasta. Keempat, platform digital harus bertanggung jawab secara etik, dengan mendesain algoritma dan sistem moderasi yang berorientasi pada keamanan pengguna, bukan semata profit. Hanya dengan membenahi sistem secara komprehensif, kita bisa membangun ruang digital yang adil, manusiawi, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
Membangun Ekosistem Digital yang Adil, Etis, dan Berkesinambungan
Menghadapi kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), solusi yang parsial tidak akan memadai. Diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya merespons gejala permukaan, tetapi juga menyentuh akar struktural, kultural, dan teknologis yang melandasi persoalan ini. Membangun ekosistem digital yang adil berarti menata ulang ulang nilai, struktur hukum, teknologi, pendidikan, dan solidaritas sosial menuju masa depan yang inklusif dan beretika.
Langkah pertama yang mendasar adalah mereformulasi kebijakan dan regulasi digital dengan kerangka keadilan gender yang progresif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kebijakan perlindungan data pribadi, harus direvisi agar secara eksplisit mengakui dan mengatur bentuk-bentuk KBGO, dengan memasukkan kategori pelanggaran, sanksi yang adil, serta prosedur hukum yang melindungi korban. Selain itu, sistem pelaporan di platform digital harus bersifat transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan korban, bukan hanya pada efisiensi teknis.
Pendidikan menjadi fondasi jangka panjang dalam membentuk ekosistem digital yang sehat. Oleh karena itu, literasi digital dan etika gender harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum sejak usia dini, agar generasi masa depan tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang kesetaraan, empati, dan tanggung jawab digital. Kampanye publik pun harus bergerak melampaui pendekatan teknis-informatif menuju pendekatan kultural-transformasional, yang menantang norma patriarki dan membangun narasi baru tentang hubungan antargender yang adil dan manusiawi.
Pada ranah teknologi, kita membutuhkan inovasi yang tidak netral, melainkan berpihak pada nilai keadilan sosial. Sistem kecerdasan buatan (AI) perlu dikembangkan dengan dataset yang inklusif, etis, dan bebas dari bias gender agar mampu secara akurat mendeteksi dan merespons ujaran kebencian serta konten berbahaya berbasis gender. Teknologi tidak hanya harus mampu mengenali kekerasan, tetapi juga harus meresponsnya secara etis melalui sistem pelindung korban yang terintegrasi—seperti aplikasi panic button, kanal pelaporan yang aman, hingga akses cepat ke bantuan psikologis dan hukum.
Namun teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan ekosistem psikososial yang kolektif dan manusiawi. Layanan konseling daring gratis, mudah diakses, dan aman secara privasi adalah kebutuhan mendesak yang harus disediakan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan. Lebih dari itu, pelatihan cyber-witness atau saksi digital menjadi upaya strategis untuk membangun jaringan solidaritas digital, di mana setiap warga bisa berperan aktif mendampingi dan membela korban.
Di tingkat global, kerja sama transnasional menjadi pilar penting dalam menghadapi karakter lintas batas dari kekerasan digital. Ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti Budapest Convention on Cybercrime harus dilengkapi dengan protokol khusus tentang KBGO. Sementara itu, aliansi multipihak—melibatkan pemerintah, akademisi, aktivis, penyintas, dan korporasi teknologi—perlu diperkuat untuk menciptakan norma global baru tentang hak digital dan tanggung jawab etis dalam ruang siber.
Pada akhirnya, solusi untuk KBGO bukan sekadar proyek teknokratis, melainkan visi filosofis tentang masa depan digital yang beradab. Dunia maya tidak boleh menjadi ruang tanpa hukum dan tanpa hati nurani. Ia harus menjadi perluasan ruang publik yang menjunjung martabat manusia, mengedepankan keadilan antaridentitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam bentuk paling modernnya. Inilah tugas generasi kita—menanamkan etika ke dalam algoritma, dan menghadirkan keadilan dalam setiap piksel ruang digital.
Menuju Etika Digital yang Membebaskan
KBGO adalah cermin dari dunia digital kita yang masih jauh dari adil dan manusiawi. Solusi bukan hanya pada tombol “laporkan”, tetapi pada perubahan paradigma: dari sistem yang pasif terhadap kekerasan, menjadi sistem yang aktif melindungi martabat manusia.
Sebagaimana sains memberi kita data, filsafat memberi kita arah. Bagaimana dengan feminisme? Ia mengingatkan bahwa tubuh, suara, dan pengalaman perempuan bukan sekadar statistik—tetapi pusat dari perjuangan keadilan yang harus kita menangkan, baik di dunia nyata maupun di ruang-ruang digital.
Menyalakan Cahaya di Ruang Digital
Pada akhirnya, perjuangan melawan KBGO bukan sekadar soal melindungi individu, tetapi tentang membayangkan kembali dunia digital sebagai ruang yang lebih manusiawi—ruang di mana martabat tidak bisa diperdagangkan, suara tidak bisa dibungkam, dan keberagaman identitas dipeluk, bukan ditakuti. Dunia digital tidak netral; ia dibentuk oleh nilai-nilai yang kita izinkan hidup di dalamnya. Maka tugas kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nuraninya. Ketika kita memilih untuk berpihak pada korban, membongkar norma-norma yang menindas, dan menanamkan etika dalam setiap algoritma dan interaksi, saat itulah kita sedang membangun bukan sekadar sistem digital yang canggih, melainkan peradaban yang layak untuk diwariskan.